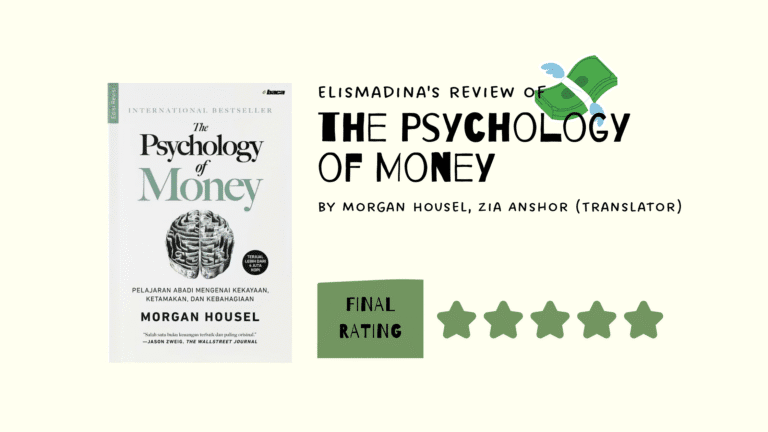My rating: 4 of 5 stars
Perempuan di Titik Nol adalah novel terjemahan dengan judul asli امرأة عند نقطة الصفر, (Emra’a enda noktat el sifr) yang ditulis oleh seorang aktivis perempuan kelahiran Mesir bernama Nawal El Saadawi. Seperti yang tertulis dalam sinopsisnya, Perempuan di Titik Nol benar-benar menguliti “borok” budaya patriarki tanpa “tedeng aling-aling” (bahasa Jawa: kiasan yang digunakan untuk menutupi rahasia atau perbuatan buruk). Sebuah ironi ketika mengetahui bahwa ada seorang perempuan yang melacurkan diri bukan karena kehendaknya sendiri, melainkan “dipaksa” oleh suatu sistem yang selama ini dipertahankan dengan kuatnya.
Novel ini mengutarakan suatu kritik sosial yang teramat pedas secara terbuka dan terus terang. Sangat lantang menceritakan bahwa hak-hak perempuan begitu timpang di masyarakat. Satu kutipan paragraf yang teramat menghujam nurani saya ialah pada saat tokoh utama, Firdaus, memutuskan untuk kembali melacurkan diri setelah dihancurkan oleh kenyataan bahwa pernikahannya tak menghasilkan apa pun selain memar dan kemiskinan. Ia memilih menjadi seorang pelacur yang sukses daripada seorang suci yang sesat (hal. 142). Meskipun demikian, ketika seorang pejabat tinggi negeri “memesan tubuhnya”, ia justru menampiknya. Bukan agar ia bisa memperoleh tawaran harga yang lebih tinggi, tapi ia sudah terlampau muak dengan segala kepalsuan yang hanya menguntungkan kaum lelaki. Seolah-olah perempuan hanyalah seonggok daging yang memiliki lubang, yang diciptakan hanya untuk melepaskan hasrat mereka.
Membaca buku ini tidak membuat saya merasa kasihan dengan Firdaus. Namun justru membuat saya berfikir bahwa dibelahan bumi lain, kaum perempuan pernah melewati masa yang sangat kelam, jauh sebelum saya lahir. Menurut saya, buku ini perlu dibaca untuk memutar ulang sejarah bahwa kaum perempuan pernah dianggap sedemikian rendahnya. Bukan dalam rangka glorifikasi, tetapi untuk meluruskan kembali pemahaman tentang feminisme itu sendiri. Mengingat belakangan ini muncul “gerakan baru” yang mengaku diri sebagai aktivis perempuan, yang nyatanya malah membuat citra feminisme itu sendiri menjadi kontraproduktif bahkan peyorasi. Sedang disisi lain, muncul pula pendapat bahwa sebagai “hamba Tuhan yang bersahaja” sudah seharusnya perempuan merendah di depan lelaki, perempuan diciptakan untuk bergantung dan berserah diri. Betapa pun ia mempunyai derajat lebih tinggi daripada seorang laki-laki, perempuan harus tetap merunduk untuk membuat laki-laki tetap tinggi.
Memang pendapat di atas menurut saya tidak keliru. Oleh karena semua tergantung dari perspektif mana kita melihat dan dari kacamata siapa kita memandang. Menjadi seorang perempuan merdeka adalah keinginan hampir semua orang dan setiap orang bebas mendefinisikan kemerdekaan menurut pemahamannya masing-masing. Jika Firdaus menilai bahwa satu-satunya kemerdekaan sejatinya adalah vonis mati yang dijatuhkan kepadanya, maka bagi saya kemerdekaan sejati adalah pada saat saya mampu membedakan antara “egoisme diri” dengan “prinsip hidup”, pada suatu kondisi yang mengharuskan saya untuk mempertahan sesuatu yang sudah selayaknya saya dapatkan.