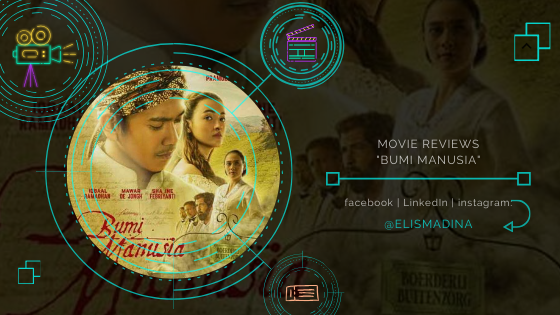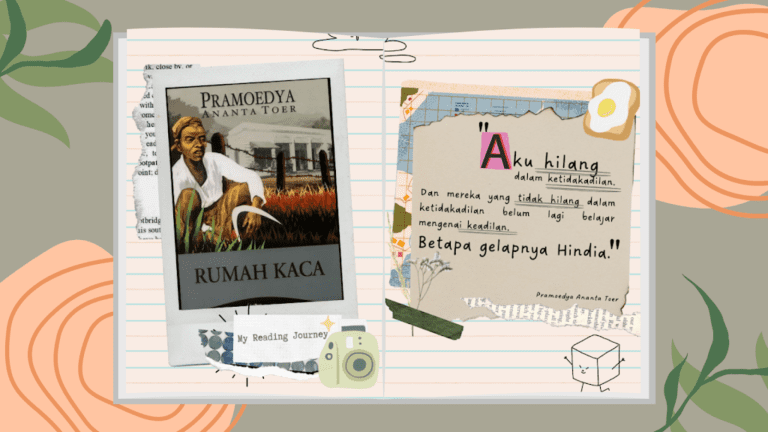Kita telah melawan Nak, Nyo. Sebaik-baiknya, sehormat-hormatnya. – Nyai Ontosoroh
Sebagai penikmat sastra, khususnya karya-karya Pak Pramoedya Ananta Toer, saya merasa film yang diangkat dari karya masterpiece Pram yang sempat dilarang untuk dibaca, bahkan pembacanya saja pun ditangkap aparat karena dianggap “kiri”, saya cukup puas dengan film produksi Falcon garapan Mas Hanung Bramantyo ini. Saya pikir keseriusan penggarapan film ini cukup terlihat dan patut diapresiasi.
Menurut saya, Ine Febriyanti sukses memerankan Nyai Ontosoroh yang karakternya begitu kuat. Awalnya saya sempat meragukan kemampuan Ine. Namun…. Dia sukses memvisualisasi Nyai Ontosoroh dengan begitu nyata. Persis seperti apa yang saya bayangkan ketika membaca bukunya. Seorang pribumi tulen yang tegak, berani, tangguh, dan tegar. Sayangnya penggambaran sosok Nyai Ontosoroh muda tidak terlalu diperlihatkan. Wajar sih, mungkin sengaja diperpendek mengingat durasi keseluruhan film ini yang hampir 3 jam.
Tim property dapat dikatakan cukup niat, mulai dari pemilihan tempat yang pas, pemilihan warna yang tidak aneh-aneh seperti pink, tosca, violet, (mana ada kan jaman dulu warna” kayak gini), dan tentu saja rumah, kereta, kertas, sandal, pendopo, dll yg menurut saya sudah sangat mendukung suasana jaman penjajahan. HANYA SAJA, semua property terlihat baru. Bagus sih, tapi seolah terlihat tidak natural. Saya membayangkannya semacam tradisi orang-orang pada umumnya yang membersihkan rumahnya dalam rangka menanti datangnya lebaran. 😂
Hal yang cukup mengganggu adalah soal dialog yang menggunakan tiga jenis bahasa, yakni Jawa, Indonesia, dan Belanda. Konsistensi dan keluwesan mengucapkan bahasa kurang terlihat natural. Satu hal yang membuatku terganggu adalah dalam scene dialog sesama orang Jawa yang menggunakan bahasa Indonesia. Ngopo gak boso jowo ae seh? Terutama konsistensi logat. Ini kan settingannya Surabaya – Wonokromo – Bojonegoro – Blora. Setahu saya logat “kon kate nyang endi?” itu digunakan oleh orang-orang Jawa Timuran sebelah timur, sedangkan logat Suroboyo-an malah menggunakan “kowe” harusnya kan “kon” hehe. Mungkin ini hal kecil, tapi sebagai orang yg tumbuh di perbatasan Jawa Timur dan Jawa Tengah, saya merasa itu sedikit mengganggu. 😃
Iqbal gimana? Kalau Anda sudah benci sama Iqbaal dari awal, sebaiknya tidak usah menonton. Karakternya Iqbal sebagai Dilan masih kerasa banget. Aku berkali-kali merasakan “geli-geli gimana gitu“, tapi nggak sampek keluar kata kasar. Saya menghormati penonton lain yang lagi konsen. Sayangnya ada nih, ibu-ibu yang duduk di samping saya, setiap scene Iqbal muncul, yang keluar dari mulut mereka pasti makian. Yang saya sayangkan, karakter Minke sebagai seorang yang intelektual, pemikir, tak pantan menyerah tidak begitu ditonjolkan, justru yang ditonjolkan adalah scene romance Minke dengan Anneliese. Meskipun demikian, menurut saya secara garis besar ceritanya masih sesuai kok. Apalagi yang pas partnya Ine emosi terus bilang (aku lupa dialognya), tapi kira-kira begini: “apakah pergundikan jauh lebih mulia daripada cinta kasih antara mereka berdua yang saling mencintai? Biadab kalian semua“. Wkwk. Saya ikutan emosi.
Komposisi cerita 50% drama 50% sejarah/hukum/perpolitikan. Ya emang gak bisa dipisahkan sih ya karena emang satu-kesatuan. Waktu di pengadilan dapet emosinya kok. Apalagi diakhir cerita. Saya nangis, tapi nggak separah pas baca bukunya. Karena yang menurut saya cukup mengganggu adalah scoring diakhir film. Kan Minke sama Ann pisah. Masa yang diputer lagu “Ku Lihat Ibu Pertiwi”? Hehehe. Kayak kurang pas aja sih menurut saya. Ibu pertiwi pun kurang pas jika dipersonifikasi sama Ann. Kenapa nggak instrumen lagu aja gitu? Seperti film pada umumnya (Yee… ngatur!!).
Yaudah itu saja. Overall 7,5/10 lah ya. Mantap! Yang belum nonton. Ya nonton aja, tapi JANGAN LUPA BACA BUKUNYA YAAAA!!!! BELI LANGSUNG SATU PAKET TERTRALOGI PULAU BURU!!!