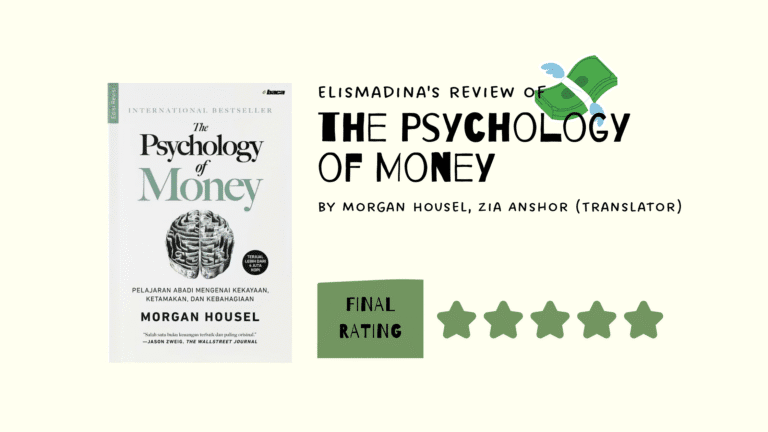My rating: 3 of 5 stars
Saya pikir, buku kedua Mas Wira ini tidak jauh berbeda (temanya) dengan buku yang pertama (Distilasi Alkena). Iya, masih seputar patah hati. Bagi saya tidak akan menjadi masalah apabila langsung membaca buku yang kedua tanpa membaca buku pertama terlebih dahulu. Untuk itu, saya tidak menaruh ekspektasi apa pun selain gambar sketsa dengan caption patah hati yang instagramable, cocok sekali digunakan sebagai konten media sosial dalam rangka memberikan kode kepada doi.
Buku Disforia Inersia masih tetap bisa bikin patah hati kok, meskipun tidak seintens buku Distilasi Alkena. Di buku kedua ini, Mas Wira tidak memaksakan dirinya untuk menggunakan kata-kata yang science geek dengan metode binomial nomenklatur. (saya dulu anak Biologi banget loh, Mas. Meskipun pada saat SMA memutuskan untuk murtad dan menjadi anak IPS. Hehe). Bahkan salah satu judul tulisan di buku ini, ada yang menggunakan bahasa Jawa, dan kadang-kadang hanya satu kata. Itu bagus Mas, bukan kamu tidak konsisten, tapi kamu mencoba keluar dari zona nyamanmu dan tidak mengungkung kebebasanmu.
Sebelum saya memberikan review, saya melihat banyak reviewer lain yang memberikan pendapat kalau buku ini membosankan. Namun, tidak sedikit juga yang merasa relate banget. fifty fifty lah. Ya, memang. Menurut saya, buku Mas Wira memang tidak bisa dinikmati apabila dihabiskan dalam satu kali duduk. Jika dipaksakan untuk dihabiskan sekaligus, kamu hanya akan mendapati lagu patah hati yang diputar berulang kali. oleh sebab itu, bacalah buku ini dengan cara diselingi buku lain, yang nonfiksi misalnya. Niscaya buku ini dapat menjadi remedy untuk hari-hari yang penat dan membosankan. Yang terpenting, melalui buku ini saya memperoleh pelajaran bahwa patah hati memang pahit, tapi entah mengapa, justru rasa pahitnya itulah yang membuat saya menikmatinya dan selalu ingin menikmatinya, melalui suatu kenangan yang saya simpan dengan rapih diingatan.