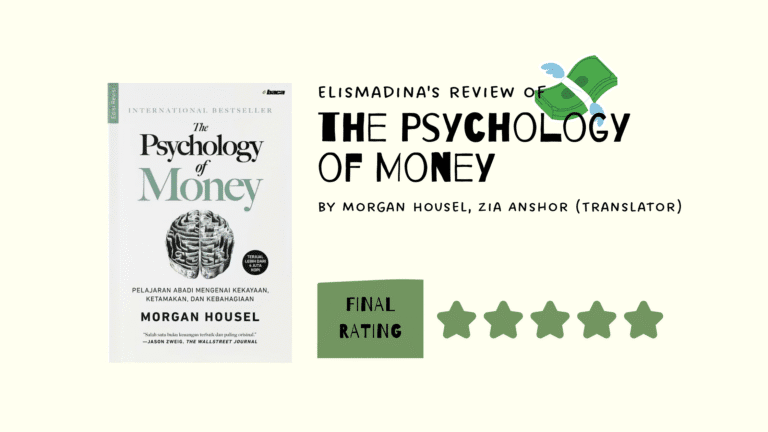Rumah Kaca by Pramoedya Ananta Toer
My rating: 5 of 5 stars
Saya pikir, Rumah Kaca sebagai buku keempat dari rangkaian Tetralogi Pulau Buru bukan bergenre romansa. Namun, buku ini berhasil membuat saya menangis di akhir cerita. Betapa tidak, hati saya terasa begitu tersayat membaca kisah ‘sang pemula’ yang kembali dari pengasingan dalam keadaan terlupakan dan dilupakan oleh bangsanya sendiri, hingga ia berpulang.
Dibanding dengan tiga buku sebelumnya, buku keempat ini tidak lagi mengambil sudut pandang Minke, melainkan sudut pandang Jacques Pangemanann dengan dua ‘n’, seorang pribumi yang bekerja untuk pemerintah Hindia Belanda sebagai seorang komisaris kepolisian Batavia yang kemudian diangkat sebagai arsiparis di Algemeene Secretarie Hindia Belanda, jabatan tertinggi yang pernah dicapai oleh seorang pribumi.
Berangkat dari sudut pandang tersebut, buku ini tidak akan jauh dari kisah seorang Pangemanann, yang di dalam dirinya mengalami dilema hebat antara idealisme sebagai seorang pribumi dengan realita kehidupan yang harus dijalaninya sebagai ‘hamba gubermen’. Satu kali ia berjanji kepada dirinya sendiri untuk membantu Minke mewujudkan kemajuan bangsa Hindia, akan tetapi di sisi lain, ia merasa ‘ke-priyayian-nya’ terhina apabila tidak mampu menuntaskan saran ilmiah mengenai apa yang harus dilakukan terhadap bangsa atau organisasi pribumi yang ‘dianggap mengancam’ bagi pemerintah Hindia Belanda.
Melalui informasi-informasi yang dikumpulkan dari lapangan, Pangemanann mulai mengolah dan melakukan analisa di atas meja kerjanya, sebagaimana ia membayangkan sedang membangun sebuah rumah kaca untuk mengawasi gerak-gerik bangsa pribumi tanpa seorang pun dari mereka tahu. Melalui kumpulan informasi itulah pembaca diajak untuk menelusuri kisah dan sejarah perjalanan pergerakan bangsa Indonesia. Terutama kisah Minke dan skenario penangkapan serta pembuangannya yang ternyata berasal dari usul ilmiah seorang Pangemanann. Dapat saya simpulkan bahwa Buku Rumah Kaca melengkapi dan menjawab kegetiran yang saya rasakan pada saat menyelesaikan Buku Ketiga, Jejak Langkah.
Awalnya peralihan sudut pandang di buku keempat ini membuat saya agak tidak nyaman. Terutama bab yang membahas dilema yang dialami oleh Pangemanann yang saya rasa cukup panjang. Harus saya akui bahwa saya cukup muak membacanya. Entah itu karena saya sudah telanjur menyukai gaya bahasa yang digunakan penulis dari sudut pandang Minke, atau karena saya telanjur benci kepada Pangemanann. Namun, perasaan tidak nyaman tersebut berhasil mereda ketika memasuki bab pertengahan buku dengan mencoba menerima dan membaca apa adanya tanpa menghakimi Pangemanann itu sendiri.
Dengan selesainya saya membaca rangkaian Tetralogi Pulau Buru ini, kembali saya sampaikan hormat dan salut yang tiada henti kepada Pram sebagai penulis. Terlepas dari kisah yang diceritakan fiksi atau nyata, saya merasa buku-buku ini setidaknya perlu dibaca sekali seumur hidup oleh siapa pun yang ingin mengenal bangsa Indonesia. Oleh karena kisah yang diceritakan tersebut tak akan lekang oleh waktu dan tetap relevan dalam kehidupan meskipun dalam bentuk lain.